Jam tangan Casio G-Shock Giez-ku menunjukkan angka 02.49 WIB pada
layar digitalnya. Aktivitas di rumah kecil dengan dua kamar, satu ruang tamu
dan satu ruang keluarga sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, kesibukan
diluar rutinitas sehari-hari. Bagasi mobil Jepang keluaran 2005 sudah terisi
berbagai barang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan yang sudah direncanakan.
Begitu sempitnya garasi rumah kecil ini, diperlukan dua kali memindahkan
perseneling ke huruf “R” untuk siap meluncur meninggalkan komplek perumahan
yang sebagian besar dihuni oleh keluarga muda. Tidak termasuk aku tentunya.
Jalan raya begitu lengang, hanya satu dua kendaraan melintas,
maklum…hari masih gelap dan bukan waktunya orang untuk beraktifitas. Jam-jam
segini merupakan waktu nyaman meringkuk di bawah selimut. Tapi 86 kilometer
adalah tujuan saat ini yang mengalahkan rasa kantuk, malas ataupun kenikmatan
lainnya.
Untuk mengusir rasa kantuk dan menghidupkan suasana kunyalakan radio
yang terhubung dengan modulator perantara file-file MP3 ke gelombang radio. Tak
ada protes maupun usul dari istriku atas lagu yang kuputar. Sesekali
berbincang-bincang atas suasana perjalanan atau masalah-masalah kecil, tapi
lebih banyak diamnya. Truk-truk dengan muatan berat sudah mulai nampak di depan
mata. Asap tebal keluar dari knalpot seiring dengan suara menderu-deru seakan
menyuarakan derita hidup yang berat dan semakin berat dengan kondisi jalanan
yang menanjak dan bergelombang. Begitu ada celah antara truk-truk tua itu, ku
tancap gas dan meliuk-liuk dengan manuver bak elang yang mencari mangsa untuk
makan siang. Tak jarang manuverku mengundang emosi para sopir truk, tercermin
dengan suara klakson yang berteriak lantang tanda kejengkelan tuannya yang
kaget dengan kemunculan kendaraan kecil di depan matanya tanpa basi-basi. Maaf
pak sopir….anda berjalan terlalu lambat…truk bapak menebarkan polusi yang jauh
diambang batas. Daripada terbayang muka sebel bapak sopir, kutancap gas agak
dalam…angka 80 sudah cukup untuk menghapus wajah sopir truk dari ketiga
spionku. Yang tersisa hanya warna hitam pekat terpantul di ketiga cermin, wakil
mataku untuk menengok ke belakang. Lamat-lamat terlihat bayangan gerbang
selamat datang Kota Salatiga. Memori otak kananku langsung bereaksi, sebentar
lagi kemudi harus aku putar ke kanan, menyusuri jalan yang sudah biasa dan
akrab aku lewati menuju titik 86 kilometer. Jalan Lingkar Selatan Salatiga,
untuk yang kesekian kalinya aku menyapamu meski tak pernah aku dengar bisikan
selamat datang darimu. Ada beberapa traffic light memenggal tubuh jalan yang
dibuat untuk mengurai kemacetan Kota Salatiga. Akupun harus berhitung antara
pedal gas dan perubahan tiga warna lampu traffic light tersebut. Hijau adalah
tujuanku jika aku sudah sampai pada tiga lampu yang setia untuk berganti warna.
Bukan tidak beralasan aku punya perhitungan seperti itu. Di tempat yang sepi
dan sangat jauh dari keramaian, kriminalitas selalu mengintip mencari
kesempatan. Adalah tidak nyaman menghitung detik demi detik menunggu pergantian
warna lampu di tempat sepi dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi.
Jalan lingkar sudah berakhir. Mudah untuk mendeteksinya. Satu dua
orang mengatur pergantian laju kendaraan dan mereka bukan petugas yang digaji
untuk menjalankan tugasnya. Hanya belas kasih dan keikhlasan para pengguna
jalan yang mereka harapkan. Begitu kaca jendela kendaraan terbuka dan tangan
pengendarapun disambut dengan senyum dan ucapan terima kasih. Aku tidak tahu
apakah senyum itu tetap ada jika tidak ada tangan yang keluar dari jendela para
pengendara atau justru umpatan dan makian yang akan mengiringi para pengendara.
Hanya mereka yang tahu. Ah…biarlah itu urusan mereka, jangan sampai pikiran dan
angan ini merusak niat ikhlas dan ungkapan terima kasih atas bantuan mereka.
Keberadaan mereka jelas-jelas sangat membantu, mengatur kendaraan dari 3 arah
supaya tidak berebut saling mendahului yang berakibat kemacetan.
Tak terlihat lagi truk-truk tua yang beriringan seolah saling
bergandengan berbagi beban yang tidak pernah dimengerti tuannya. Sesekali
sepeda motor dengan muatan sayur sayuran melaju dengan kecepatan tinggi seakan
berebut rejeki. Terpikir olehku, jam berapa mereka bangun, sejak kapan
rutinitas itu mereka mulai, enjoy-kah dengan kondisi yang mereka jalani atau
karena tak ada pilihan lain. Hidup ini beragam tapi banyak anak manusia yang
tidak bisa memilih atas keberagaman roda kehidupan. I have no choice, hanya ungkapan itu yang keluar dari mulut-mulut
dengan pola pikir sederhana.
Kulirik barisan angka digital pada LCD dashboard mobil Jepangku,
04.04. Sebentar lagi panggilan untuk bermunajat dengan Sang Kholik akan
berkumandang. Masih ada waktu untuk merayu RPM mobil ini tetap dikisaran angka
3000-an tak perlu mendekat ke putaran 4000-an, tak ada yang harus kukejar dan
juga tak ada rasa iseng menghampiri benakku untuk menaikkan adrenalin dengan
sedikit kebut-kebutan di jalan yang lebar, sepi dan mulus. Jangan….sekali-kali
jangan….konsentrasi mulai menurun, rasa kantuk ini membombardir mataku. Gerbang
pincang tinggal beberapa puluh meter lagi. O iya…kenapa gerbang itu aku kasih
nama pincang, karena gerbang itu mempunyai sisi yang berbeda satu sama lainnya.
Beberapa waktu lalu gerbang itu tidaklah pincang, simetris layaknya
gerbang-gerbang selamat datang sebuah kota.
Kemakmuran serta kepintaran manusia yang membuat gerbang itu pincang,
pelebaran jalan memaksa salah satu gapura gerbang merelakan separo sisinya di
amputasi, hingga tinggal bagian yang pendek. Program pada otak kananku langsung
running, pertigaan pertama belok
kiri. Tak kulihat pengamen pertigaan yang selalu mengucapkan terima kasih atas
receh yang kuberikan sebelum dia menyanyi dengan gitar kecilnya, matur nuwun pak, kulo dereng nyanyi sampun
panjenengan paringi arto, mugi-mugi kathah rejeki kaliyan lancar wonten mergi…Amin….akupun
mengiyakan doanya.
Jalan berkelok-kelok dengan lubang di sana-sini memaksaku untuk
menajamkan mata meski serasa ada beban berkilo-kilo di setiap ujung kelopak
mataku. Terlepas dari jalan yang kondisinya bak pipi gadis belia yang penuh
dengan lubang-lubang jerawat yang tidak dikelola dengan baik, masuk di kawasan
militer. Garis kejut yang sengaja di pasang seolah-olah mengingatkanku bahwa
aku berada di kawasan penjaga kedaulatan negara dan bangsa. Tinggal satu lagi
keberuntunganku dipertaruhkan, satu traffic light yang menuntut kesabaran,
angka yang mengiringi warna hijau dimulai dengan bilangan 15 sangat tidak
imbang dengan bilangan hampir satu setengah menit yang menemani bulatan warna
merah. Begitu terlepas dari sergapan bulatan merah, kuinjak pelan-pelan pedal
gas mobil Jepang-ku.
Kulihat kubah putih yang begitu megah, dari sisi selatannya berjalan
satriwati-santriwati seusia kedua bidadariku dengan mukena warna putih. Adakah
dua diantara mereka merupakan buah hatiku, amanah yang Allah titipkan padaku…atau
kedua bidadariku sudah berada di dalam bangunan megah dengan kubah putihnya?
Kubelokkan setang kemudi mobil Jepang-ku berseberangan dengan gerbang
bertuliskan Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam, Pabelan, Sukoharjo. Kupilih
tempat yang teduh di waktu siang hari dan tidak mengganggu kendaraan lain. Dan….perjalanan menuju titik 86 kilometer telah berakhir.
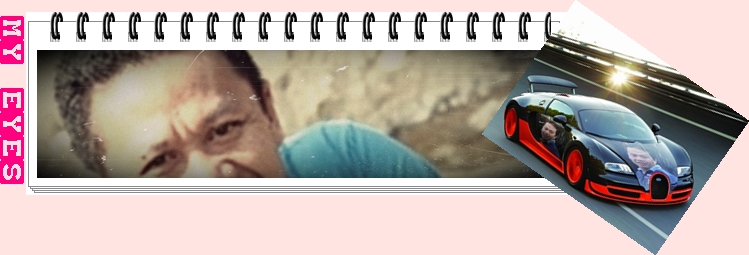

No comments:
Post a Comment